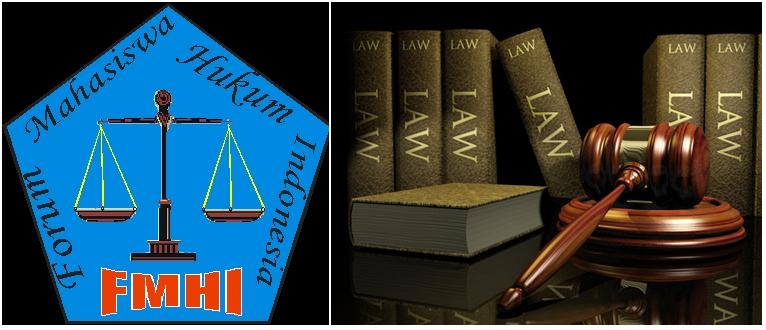HAM BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM
A. PENDAHULUAN
Dalam rentang peradaban dunia, menguak eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal itu sama menariknya ketika manusia membicarakan eksistensi negara sebagai suprastruktur kehidupan sosial demi keberlanjutan eksistensi manusia itu sendiri. Korelasi ini bisa dipahami, sebab dalam proses interaksi itu, manusia selalu dihadapkan pada dinamika sosio-politik dan ekonomi yang bertolak tarik dengan ego-kekuasaan atau naluri kolonialisme yang praksisnya kerap despotis dan merendahkan. Titik persingungan dan ketegangan itu pula, dalam sejarah, merupakan pembuka reformasi politik eropa (akhir abad 18) lalu menjadikannya sebagai momen bersejarah lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia.
Kelahiran HAM membuka kembali mata, hati, dan pikiran manusia (kesadaran) tentang hakekat dan sejatinya ia sebagai manusia, mahkluk Tuhan yang sempurna, berakal budi dan nurani yang memiliki kemampuan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Posisi biner manusia menjadikan diri manusia makhluk multidimensional yang saling bergantung dan terpusat pada Yang Maha Tidak Bergantung yakni Tuhan. Dalam perspektif Teologis, Tuhan merupakan preferensi hidup bagi dimensi lahiriah maupun jasmaniah; pribadi maupun sosial, makrokosmos, metafisis, atau transendental maupun mikrokosmos yang fisis (keimanan) melalui Kitab dan utusan yang dikehendakinya. Tuhan yang dalam sistem kepercayaan dikenal dalam institusi keagamaan sebagai sang Pencipta telah mengkarunia manusia kewajiban dan hak secara seimbang agar manusia dapat hidup dan mewujudkan kehidupannya dengan baik, damai dan sejahtera lahir dan bathin. Berkaitan dengan hal itu, sejatinya agama adalah pencarian spritual manusia tentang hakekat kebenaran dan kedamaian dirinya dan Tuhan yang terjadi secara evolutif. Dalam proses pencarian dan kebenaran itu maka agama dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati oleh institusi apa dan manapun. Karena itu dalam konfigurasi ketatanegaraan, HAM beragama mempunyai posisi yang sangat penting. Bagaimanapun juga HAM beragama akan menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Persoalan yang muncul kemudian bagaimana posisi agama dalam konteks negara? Atau posisi agama dalam konteks hukum? Tulisan ini ingin mengkaji lebih dasar bagaimana HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum.
B. NEGARA, AGAMA, DAN HAM
Dalam wacana sejarah atau filsafat hukum, relasi negara dan agama sebagai satu entitas politik pernah tumbuh dan berkembang pada Abad Pertengahan (Abad XV sM). Latar belakang perpecahan raja-raja yang disulut kemelut politik dan keserakahan duniawi yang kemudian disatukan oleh kekuasaan imperium Romawi dengan politik unitary melahirkan pemikiran-pemikiran fundamental spiritual dalam konsep kenegaraan baik di dunia Timur maupun Barat.
Ajaran ini mengatakan bahwa kedaulatan negara secara utuh dan mutlak hanya milik Tuhan. Tuhan adalah hakekat satu-satunya yang paling luhur, pencipta dan penguasa segala hakekat yang ada dan tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan negara dikenal sebagai ajaran Teokrasi. Sumber kedaulatan yang berasal dari Kitab Suci memberi otoritas politik kepada Paus sebagai pemangku agama Katholik sekaligus pemangku negara.
Menurut Augustinus (354-430 sM) praktik kenegaraan Romawi adalah satu konsep negara buruk yang penuh kegelapan akibat keserakahan penguasa (Civitas Terrena). Dan, ia akan menjadi baik apabila seluruh sendi kehidupan negara kembali kepada ajaran Tuhan dan mendapat pengampunan melalui pemangku otoritas-Nya (Civitas Dei). Karena itu, Augustinus menganjurkan perlunya pelembagaan agama dalam negara sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Konstantin Theodisius di Konstantinopel.
Disempurnakan oleh Thomas Aquino (1225-1274 M), Ia mencoba merumuskan ajaran kenegaraan ini sebagai satu tatanan hukum bagi golongan Katholik. Alam pikirannya yang sangat dipengaruhi oleh alam pikir Yunani memperlihatkan pertautan Principia Prima dengan hukum Tuhan dan hukum manusia sebagai hukum kongkret yang positif. Menurutnya, sebuah tatanan hukum yang baik adalah hukum yang mendasarkan pada hukum yang tertinggi yang disebut Lex Aeterna atau hukum abadi. Lex Aeterna adalah hukum yang bersumber dari rasio Tuhan yang Maha Mengatur dari segala yang ada. Di dalamnya terkandung hukum-hukum universal yang sejalan dengan kausa Alam dan aqal sehingga dinilai abadi. Kedua, hukum yang diwahyukan kepada manusia yang bersumber dari rasio Tuhan (Lex Divina). Hukum dalam tingkatan ini adalah hukum yang dirumuskan dalam bahasa Nabi melalui pewahyuan. Tingkatan ketiga, personifikasi hukum wahyu ke dalam rasio manusia (Lex Naturalis). Tingkatan keempat yakni hukum yang paling kongkret (hukum positif) merupakan penjelmaan dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Ditambahkannya pula bahwa setiap penciptaan hukum harus mendasarkan pada tujuan ideal yang ingin dicapai yakni kemuliaan abadi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berubah dan memiliki tabiat kepada kemuliaan abadi.
Namun otoritas agama yang penuh pada dimensi kehidupan negara dan masyarakat mengakibatkan terampasnya kebebasan warga. Pandangan konservatif ini menegaskan bahwa setiap persoalan baik duniawi maupun ukhrowi telah menjadi satu ketetapan Tuhan sementara manusia sendiri tidak diberi otoritas untuk merubahnya sehingga ruang berpikir kritis tidak mendapat tempat sama sekali. Dependensi warga pada otoritas Paus yang memiliki dualime kekuasaan itu sejatinya telah merendahkan harkat dan martabat yang hakikinya anugerah Tuhan untuk memuliakan manusia.
Di abad yang sama, peradaban Islam juga menunjukkan satu kecenderungan yang sama. Hampir semua teologi Islam dan orientalis sepakat bahwa praktik kehidupan negara yang Islami terhenti setelah berakhirnya pemerintahan Khilafah Rasyidin Umar bin Khatab. Revolusi sosial yang dilakukan Rasulullah melawan segala bentuk diskriminasi ras, gender, perbudakan, komoditi ritual, sistem perdagangan yang kapitalistik dan tidak manusiawi sempat membuat satu perubahan politik besar dalam tatanan kehidupan bernegara masyarakat Arab pada saat itu dan menjadi satu bentuk negara agama ideal dalam konstelasi pertumbuhan ideologi dunia. Di abad klasik (650-1250 M), Islam di masa Rasulullah memiliki keunikan dalam mengorganisir kehidupan masyarakat Arab yang plural di bawah konstitusi Piagam Madinah. Pluralitas keberagamaan, aliran kepercayaan, etnik, suku, class social, dan stratifikasi ekonomi dan politik mampu disatukan dalam satu ikatan hidup bersama yang damai, toleran, saling menghargai dan menghormati, egaliter, dan saling melindungi bahkan saling mewarisi. Louis Gardnet sebagaimana dikutip Muhammad Tahir Azhary menyebutkan bahwa ciri yang paling menonjol adalah spirit egaliter dalam kehidupan negara tanpa dominasi kependetaan dalam sistem pemerintahan. Menurut Arent Jan Wensinck, petunjuk penting adanya ciri tersebut diperoleh dari sejumlah hadis Al-Bukhori dan Muslim, dan mencantumkan ihtisar tentang life of constitution di dalam Bab Fada’il al-Madinah.
Berbeda dengan negara model kepausan di mana kerajaan Paus mendominir rakyat jelata, Negara Islam yang didirikan Rasulullah, menurut Taha Husain, bukanlah negara teokrasi. Islam melarang kependetaan dan stratifikasi sosial berdasarkan kasta kependetaan. Islam adalah agama yang menekankan ketauhidan, kerasulan, persamaan dan keadilan. Keadilan yang dualistik (dunia dan akhirat) tidak akan merampas kebebasan manusia, menguasai dan membelenggu inisiatif dan kreatifitasnya. Tuhan telah melengkapi manusia dengan akal dan nurani untuk membingkai kebebasannya secara bertanggung jawab. Abul Ala Maududi menyimpulkan dari relasi di atas sebagai Teo-demokrasi. Muhammad Tahir Azhary menyebutnya dengan Nomokrasi Islam.
Al Qur’an sebagai sumber tertinggi hukum negara telah berbicara banyak tentang HAM. Terdapat sekitar empat puluh ayat yang bicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya: “Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.” Al-Qur’an mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat yang diungkapkan dengan kata-kata: ‘adl, qisth dan qishas. Al-Qur’an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.” Al Qur’an Juga bicara kehormatan dalam sekitar dua puluh ayat. Al-Qur’an menjelaskan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya: “… Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa di antara kamu.” Terakhir pada haji wada’, Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu Nabi saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.
Sepeninggal Nabi, persoalan penting yang mengemuka adalah persoalan transisi dan legitimasi politik pemerintah pengganti Nabi. Persoalan ini menimbulkan perpecahan dan penurunan kualitas pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai Islam sebelumnya. Bahkan konflik perpecahan itu melahirkan aliran-aliran teologi atau kalam seperti Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah, Jabbariyah, dan Qodariyyah sebagai ekspresi kekecewaan ataupun dukungan untuk melegitimasi elit yang berkuasa. Aliran-aliran tersebut kerap menggunakan hadis atau mengadakan hadis untuk menjustifikasi penguasa yang didukungnya. Perpecahan ini mulai marak ketika awal Pemerintahan Usman, Ali, dan Bani Umayyah yang typikal pemerintahannya didominasi oleh golongan baru atas dasar relasi yang paternalistik, nepotis, kolutif, dan elitis. Terbunuhnya Usman menjadi malapetaka besar pemerintahan Islam di masa Ali yang terus dibayangi perpecahan dan pemberontakan. Meski Ali sendiri tidak diragukan kadar keimanan, integritas moral, dan kompetensi politik dan kenegarawanannya akan tetapi konspirasi yang dilakukan golongan elit baru membuat dirinya tak kuasa menentang arus dan mengakhiri masa pemerintahannya sendiri.
Di masa Umayyah, praktik pemerintahan semakin jauh dari nalai-nilai Islam. Sistem kekuasaan yang monarkhi dan despotis memanfaatkan cara-cara imperialis dalam hubungan perdagangan (meniru model kekaisaran Bizantium dan Sassanid) dan perluasan kekuasaan. Tradisi egaliter dan humanistik berubah menjadi feodal. Hitti sebagaimana dikutip Asghar, mengatakan, “Seratus tahun setelah meninggalnya Muhammad, pengikutnya menjadi penguasa kekaisaran yang jauh lebih besar dibanding Romawi pada puncak kejayaannya.” Kehidupan yang serba gelamor menjadikan Mekkah dan Madinah yang tadinya tempat suci menjadi pusat hiburan dan perjudian. Upaya mengembalikan kondisi awal dan memperkokoh landasan moral negara telah banyak dilakukan oleh kaum Kharijit dan para ulama puritan, namun usaha itu tidak berhasil. Setelah turunnya Umayyah, Abasiah mengorganisir pemberontakan bersenjata dan berhasil merebut kekuasaan dengan bantuan kalangan Persia, terutama dari propinsi Khorasan. Bani Abasiah tidak lama kemudian mengkonsolidasi posisi mereka dan berupaya melegitimasi kekuasaan mereka dengan dukungan para ulama. Meskipun peralihan kekuasaan tersebut didukung akan tetapi fatwa ulama sendiri tetap tidak mengizinkan praktik pemberontakan. Dari praktik pemerintahan itu semua terlihat bahwa sepeninggal Rasulullah pemerintahan Islam dijalankan dengan penuh panorama yang berujung pada praktik feodalistik menggantikan spirit egaliter selama ini. Agama yang hanya menjadi tameng dan alat legitimasi kekuasaan menimbulkan trauma dalam sehingga melahirkan priksi di kalangan ulama untuk menarik agama keluar dari otoritas negara.
Meski kekecewaan telah melahirkan sekulerisme negara di Abad Modern akan tetapi krisis sosial, politik, dan ekonomi dunia di tengah arus globalisasi membuat perbincangan relasi agama dan negara menjadi menarik kembali. Ulrich Beck sebagaimana dikutip Kaelan, mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami ‘deteritorialisasi’. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Prinsip kebebasan dalam sistem negara demokrasi sekuler berpengaruh secara cepat terhadap negara lain di dunia, termasuk negara Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Kasus Yeland Fosten tentang karikatur Nabi Muhammad menimbulkan suatu benturan peradaban antara sistem kebebasan versi sekuler dan negara Berketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara itu Anthony Giddens menamai proses globalisasi sebagai ‘the runaway world’. Menurutnya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Robertson mengingatkan bahwa globalisasi merupakan ‘compression of the world’ yaitu menciutnya dunia dan menurut Harvey sebagai proses menciutnya ruang dan waktu ‘time-space compression’, karena intensivikasi dan mobilitas manusia serta teknologi. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam kehidupan kebangsaan, yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan (state centric world) kepada dunia yang berpusat majemuk (multy centric world). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae sebagaimana dikutip Kaelan bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.
Bahkan A.M. Hendropriyono dalam karyanya Nation State di Masa Teror, bahwa di era globalisasi ini negara-negara yang sedang mengembangkan proses demokratisasi akan mendapatkan tantangan yang sangat hebat, terutama ancaman terorisme yang menyalahgunakan kesucian agama. Nampaknya sinyalemen A.M. Hendropriyono ini diperkuat oleh pandangan Bahmueller bahwa dalam proses demokratisasi harus diperhatikan (1) the degree of economic development, (2) a sense of national identity, (3) historical experience and (4) element of civic culture. Jadi pengembangan demokrasi harus diperhatikan tentang bagaimana kondisi ekonomi dalam suatu negara, dasar filsafat negara sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, bagaimana proses sejarah terbentuknya bangsa itu beserta unsur-unsurnya.
Konstatasi yang layak diperhatikan adalah sinyalemen dari Naisbitt sebagaimana dikutip Kaelan, bahwa di era globalisasi tersebut akan muncul suatu kondisi paradoks, di mana kondisi global diwarnai dengan sikap dan cara berpikir primordial, bahkan akan muncul suatu gerakan ‘Tribalisme’ yaitu suatu gerakan di era global yang berpangkal pada pandangan primordial yaitu fanatisme etnis, ras, suku, agama, maupun golongan. Bahkan Hantington dalam The Clash of Civilization menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadinjya suatu benturan peradaban, yang tidak menutup kemungikinan juga berakibat pada adanya konflik horizontal. Bahkan ditambahkan oleh A.M. Hendropriyono, bahwa pada panggung politik dunia benturan peradaban itu mencapai klimaksnya antara dua peradaban besar yaitu fundamentalisme politik Islam dengan kekuasaan kapitalisme neoliberal dengan kekuasaan kerasnya (hard power) di bawah komando Amerika serikat. Kita sadari atau tidak bahwa isu global tentang radikalisme agama dalam negara akan berpengaruh terhadap negara Indonesia, terutama dalam hubungan negara dengan agama. Bahkan adakalanya persoalan itu ditarik dengan memutar jarum jam ke belakang, yaitu persoalan muncul kembali pada kemelut tarik-menarik antara Negara agama dan Negara sekuler, sebagaimana dibahas oleh para founding fathers kita dahulu. Pada hal kita lupa bahwa suatu kesepakatan filosofis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia.
B. HAM dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
Dalam kajian Filsafat Ilmu Hukum bicara HAM berarti bicara persoalan mendasar atau hakekat dari HAM itu sendiri. Jawaban atas persoalan ini sama sulitnya ketika bertanya, apa itu hukum? Karena sejatinya obyek yang ditanyakan adalah penelusuran dari sesuatu asal dari sesuatu yang ada sampai menjamah pada esensi bukan hanya sesuatu yang partikular ditangkap oleh organ inderawi berdasarkan pengalaman.
Secara fenomenologis, HAM yang kita kenal adalah HAM yang tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, akan tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Deskripsi ini dapat menyingkap apa yang ingin dicapai oleh HAM dalam artian teleologis, tetapi tidak merinci HAM mana yang ada,atau apakah HAM itu.
Dalam dinamika kenegaraan terdapat piagam-piagam HAM seperti Magna Charta (15 Juni 1215 ), Petition of Rights (1628), Hobeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689 ), Declaration of Independence di Amerika Serikat, Declaration des Droits de L’Homme et Du Citoyen, Perancis (1789), yang kemunculannya bermula dari teori hak-hak kodrati. Eksistensi HAM itu dipahami sebagai hak kodrati yang diberi alam sebagai hakekat kodrati manusia, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dari harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.
1. Hukum Alam
Ada dua masa perkembangan hukum kodrati yang dapat menerangkan eksistensi HAM termasuk HAM beragama. Pertama, hukum kodrati jaman kuno yakni Abad Pertengahan yang direpresentasikan oleh para filsuf kristiani dan Islam. Filsuf kristiani di antara yang terkemuka adalah Santo Thomas Aquino/Aquinas. Islam diwakili oleh Ibnu Abi Rabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pandangan Thomistik mengenai hal ini mempostulatkan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Posisi masing-masing individu dalam kehidupan telah digariskan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada Tuhan. Tuhan, dalam ajaran ini, identik dengan keadilan. Jaminan hukum oleh penguasa terhadap hak-hak kodrati baru dipandang adil apabila tidak bertentangan dengan prinsip hukum alam dan hukum yang tertinggi sebagai hukum Tuhan yang abadi. Dengan demikian meskipun individu memiliki otonomi atas hak-haknya yang diberikan Tuhan akan tetapi penggunaan hak itu dibatasi oleh otoritas Paus sebagai wakil Tuhan.
Di dunia Islam, hukum kodrati sebagai hukum kepasangan atau keseimbangan dalam terma alam juga merupakan bagian dari hukum Tuhan. Ibnu Abi Rabi’ yang menulis banyak tentang konsep kenegaraan “monarkhi” yang banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani mengatakan bahwa Allah telah mencipatakan manusia dan seisi alam dengan watak yang cenderung komunal, yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ibnu Abi Rabi’ sepakat dengan pemikir Yunani (Plato dan Aristoteles) tentang komunalisme watak manusia hanya ia mencoba mengaitkan itu semua dengan eksistensi Tuhan pemberi hak dan kewajiban dengan prinsip-prinsip hidup yang ditentukan dalam Al Quran. Menurutnya, posisi penguasa sebagai khalifah fil ardhi bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat dari Tuhan dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan.
Landasan ajaran ini sepenuhnya teistik yang artinya menekankan pada keimanan kepada Tuhan. Tetapi tahapan selanjutnya memutuskan relasi transendental itu dan membuatnya menjadi suatu produk pemikiran sekuler yang rasional. Dalam risalah Grotius, De Lure Belli ac Pacis, ia berargumen bahwa eksistensi hukum kodrati, merupakan landasan semua hukum positif, dapat dirasionalkan melalui landasan non empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis tersebut terhadap persoalan hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan “nalar yang benar” dan kesahihannya tidak bergantung kepada Tuhan. Dengan menggunakan nalar yang benar model Grotius dapat dipahami suatu perkembangan teori hak kodrati atau hak individu. Disempurnakan oleh John Locke bahwa hak-hak kodrati manusia yang seutuhnya penuh dan universal dalam prakteknya absurd dan spekulatif (penuh ketidak pastian). Karena itu Locke menawarkan satu konsep kongkret manifestasi hak-hak kodrati ke dalam Kontrak Sosial (ikatan suka rela), yang dengan bentuk itu penggunaan hak tak dapat dicabut oleh penguasa negara. Penggunaan teori kontrak sosial ini melandasi dan dapat menjelaskan Revolusi Gemilang Inggris tahun 1688. Akan tetapi seiring konstelasi politik yang berubah di mana arus modernisasi membawa isu-isu kemanusiaan, ekonomi, liberalisme, neoliberalisme maka hak-hak kodratipun mengalami dekontruksi ke arah pemikiran yang positifistik demi menjawab kepastian hukum bukan isu HAM itu sendiri. Karena bicara hak-hak kodrati yang mendasarkan pada hukum alam selalu bermuara pada etik moral yang dalam perkembangannya terbentur dengan kompleksitas negara yang ingin memelihara unitary sekaligus membutuhkan unifikasi hukum.
2. Hukum Positif
Sementara para teoritikus hukum kodrati menurunkan gagasan tentang hak itu dari Tuhan, nalar dan pengandaian moral yang apriori maka teoritikus hukum positif berpendapat bahwa eksistensi dan isi HAM dapat diturunkan dari hukum negara. Melihat sisi HAM yang apriori sehingga mengundang spekulasi implementasi HAM dalam ranah politik yang absurd yang tak dapat menjawab bagaimana suatu sistem hukum yang sistemik yang dapat dibangun dari hukumkodrat maka perlu merumuskan kembali HAM dalam ranah hukum yang riil yang lebih menjamin HAM dalam konteks negara. Pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham sebagaimana dikutip Todung Mulya Lubis, yang mengatakan,
“….rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsens, natural and impresicible rights rethorical nonsens, nonsens upon still.”
Letak perbedaan yang paradoksal dengan pemikiran sebelumnya adalah bahwa hak-hak kodrati yang lahir dari sebuah atribusi hukum positif semata-mata kehendak pembentuk hukum (penguasa) yang berdiri secara netral untuk tujuan yang ideal. Kehendak hukum adalah kehendak rakyat dalam logika demokrasi representatif Roussoeu yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang ada bukan seharusnya. Hukum yang ada adalah hukum yang positif yang keadilan hukum diukur dari, mengutip istilah Hans Kelsen, sebagai norma-norma yang diturunkan dari staatsfundamentalnorm atau grundnorm norma hukum tersebut. Staatsfundamentalnorm adalah norma tertinggi negara sebagai hasil kesepakatan politik dan mengandung nilai-nilai universal karenanya harus dipandang sebagai Prima Facie yang kebenarannya bersifat mutlak. HAM lahir sebagai satu bentuk kontrak sosial yang dituangkan di dalam konstitusi.
Agar tidak sekedar normverbis semata maka Hume dilanjutkan oleh Jeremy Bentham mengembangkan nilai universal hak-hak kodrat ke dalam relasi kemanfaatan atau kebahagiaan sosial dengan mengukurnya ke dalam nilai utility dari hukum yang dibentuk. Menurutnya, manusia dalam kehidupan dihadapkan pada dua keadaan yakni kebahagiaan dan penderitaan, dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua, nasib manusia akan lebih baik. Oleh karena itu, tujuan utilitas adalah meningkatkan seluruh stok bagi kesenangan manusia, yang dapat dihitung secara matematis. Berdasarkan pemikiran ini maka kebebasan HAM harus dijamin oleh hukum agar tiap-tiap individu dapat menentukan orientasi kebijakan negara yang dapat memberikan kebahagiaan lebih banyak orang.
3. ANTI UTILITARIAN
Pandangan ini lahir sebagai antitesis dari sistem nilai unititarian yang mengukur maksimalisasi kebahagiaan dari kuantitatif mayoritas yang menikmati akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana dengan minoritas yang terabaikan atau tidak menikmati keadilan dari kebahagiaan yang dituju. Utilarian tidak dapat menjawab hal itu dan cenderung berapologi pada konsekuensi sistem demokrasi yang dipilih.
Hal yang sama terjadi pada persoalan kebahagiaan yang ingin diberikan pada Negara Agama vis a vis Nation State yang sekuleris. Di satu sisi berupaya memaksimalisasi kebahagiaan dengan mengutamakan agama mayoritas namun di sisi lain ingin memaksimaliasi kebahagiaan humanisme dengan mengisolir agama dalam ranah negara. Kedua konsep tersebut memberi dampak pada ketidakadilan minoritas yang dalam lambat laun akan melahirkan satu gerakan primordial yang dalam bahasa Huntington The Clash of Civilization. Menurut Dworkin dan Nozick sebagaimana dikutip Scott Davidson ada kalanya perbedaan merupakan hal yang berbeda karena itu tidak dapat disamakan. Kritik kedua tokoh ini menyatakan utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Minoritas atau individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan kurang dihiraukan, dan sebagai akibatnya, mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya. Sebagai contoh mereka tambahkan, isu homoseksual. Mayoritas rakyat dalam suatu negara mungkin menganggap praktek homoseksual dilarang dalam ajaran agama yang diyakini, merupakan perilaku buruk dan menjijikkan sehingga mereka ingin melarangnya dalam undang-undang. Keingin ini jelas memenuhi aksioma sentral dari utilitarianisme, karena memaksimalkan kebahagiaan mayoritas. Namun dalam negara demokrasi yang pluralistik, pendirian semacam ini jelas tidak dapat dipertahankan. Karena itu kecenderungan utilitaria melahirkan tirani mayoritas.
Teori Nozik menuntut suatu komitmen ontologis terhadap jenis moralitas dan organisasi sosial tertentu. Dalam teorinya, ia mempostulatkan sekelompok pria dan wanita yang dalam suatu keadaan alamiah bergabung membentuk negara minimal (minimal state). Negara minimal ini tidak hanya berlandaskan pada ajaran-ajaran moral tertentu, malahan ia juga merupakan salah satu ajaran moral tertentu. Menurutnya, memiliki negara yang fungsinya lebih luas ketimbang negara minimal yang fungsinya terbatas sekedar sebagai “penjaga malam”, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, dalam hal ini berarti bertentangan dengan moral.
Tesis Nozik jelas sangat teoritis dan implementasinya dengan memaksimalkan kebebasan yang tersedia bagi semua individu dalam sistem negara liberal kapitalistik akan semakin memantapkan ketimpangan sosial yang ada. Padahal, kebebasan individu yang maksimal hanya mungkin bila negara tidak ada.
4. Realisme Hukum
Aliran filsafat ilmu hukum ini tidak lagi mempersoalkan apa itu hukum, bagaimana HAM itu ditur oleh hukum, melainkan apa dan bagaimana hukum HAM itu senyatanya berlaku atau berfungsi bagi ketertiban hidup masyarakat. Llewelyn mengatakan teori ini sebagai bagian dari paket dari studinya mengenai proses dan interaksi di antara kebijakan, hukum dan lembaga-lembaga hukum. Bahkan Pound telah membuat satu resep untuk pengesahan dari keinginan manusia, tuntutan manusia serta kepentingan sosial melalui suatu rekayasa sosial. Namun ia tidak mengidentifikasi suatu mekanisme atau metode yang dapat memprioritaskan hak-hak individu, baik dalam kaitannya dengan hak-hak itu satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan sasaran masyarakat. Myres McDougal dan rekan-rekannya telah mengembangkan suatu pendekatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang sarat nilai dan berorientasi pada kebijakan, berdasarkan pada nilai-nilai luhur perlindungan terhadap martabat manusia.
5. Relativis Kultural
Teori ini merupakan antitesis dari teori-teori hak-hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (different ways of being human).
Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, “..that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings.”
6. Marxis
Menurut Marx, hak-hak kodrati atau HAM yang bersumber pada hukum alam adalah idealistik dan ahistoris. Karena itu klaim kaum revolusioner borjuis abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan.
Dalam teori Marx, hakekat seorang individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini di dalam masyarakat kapitalis, di mana alat produksi dikuasi oleh kelas yang berkuasa, adalah mustahil karena hal itu mengakibatkan teralienasinya kelas buruh. Marx menambahkan, potensi sejati manusia hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial. Tetapi ini hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang benar-benar komunis di mana semua alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi konflik sosial. Tetapi, masyarakat komunis semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui suatu revolusi kaum proletar industri. Revolusi ini selanjutnya akan mengubah dirinya menjadi diktator proletar dan, melalui kekuatan ekonomi dan sejarah, akan mengakibatkan pudarnya negara. Namun sebelum pudarnya negara, partai revolusioner harus menduduki posisi pelopor sambil menggunakan negara dan lembaga-lembaganya untuk transformasi masyarakat itu. Pada titik inilah muncul konsep marxis mengenai hak. Selama periode tranformasi itu, tidak ada hak individual karena hak ini egoistis, berdasar “hak milik” yang borjuis; hanya ada hak legal, yang diberikan oleh negara dan diarahkan untuk peralihan dari negara komunis menuju masyarakat komunis. Dengan demikian, karena diarahkan untuk mereduksi alat produksi agar berada di bawah pengawasan bersama, maka hak-hak ini hanya mungkin bersifat sosial dan ekonomi. HAM beragama tidak diakui bahkan dilarang. Sebab, agama dipandang sebagai candu masyarakat yang dapat mengalihkan persoalan dari persoalan penindasan oleh kapitalisme yang sesungguhnya.
7. Pancasila
Dalam perspektif Pancasila, terdapat hubungan piramid antara manusia, alam, dan Tuhan. Tuhan merupakan Prima Facie dalam membangun relasi keduanya secara seimbang dengan penghormatan harkat dan martabat semua makhluk dalam rangka kemaslahatan sosial (rahmatan lil’alamin). Dalam sistem hukum, hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Alenia Keempat di mana nuansa religiusitas mewarnai nilai-nilai pancasila yang ikut membingkai pembentukan NKRI. Bingkai ini kemudian menjadi ukuran Pancasilaime yang menurut Sihombing dapat dilihat dalam dua cara yakni konsepsionil, dan tingkah laku (kebudayaan)nya. Konsepsionil berkaitan dengan integrasi sila-sila Pancasila, sedangkan sikap berkaitan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk meujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29). Dan dipertegas lagi dengan Pasal 28E dan 29 ayat (2) yang intinya menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan; dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.” Pasal-pasal ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk menjamin HAM beragama dan HAM setiap orang termasuk jama’ah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
Dalam Pasal 28I UUD 1945 berbunyi:
Ayat 1: “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Ayat 2: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.
Terhadap dalil di atas, bukan berarti Indonesia mengadopsi HAM Beragama yang tanpa batas melainkan berdasarkan Pasal 28 J, HAM harus berada dalam bingkai sosial keberagamaan yang lain, yang tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.
Dalam konteks itu, Pancasila merupakan ideologi netral dan tengah atas religius state dan seculer state. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Dalam Falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah Negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.
Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan YME harus melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya masing-masing. Dengan demikian, lanjut, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.
C. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HAM beragama dalam tinjauan filsafat ilmu hukum bertumpu pada cara pandang dalam melihat hakekat eksistensi HAM itu sendiri. Pandangan hukum alam memandang HAM Beragama bersifat otonom sebagai konsekuensi dari kodrati yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan manusia. Dalam pemikiran modern hak-hak kodrati yang bersumber dari hukum alam itu dapat dirumuskan secara humanistik melalui nalar rasional tanpa harus mengkaitkan dengan keberadaan Tuhan.
Namun sifatnya yang apriori dan tak dapat dirumuskan secara sistemik dalam menjawab kepastian hukum maka pandangan Hukum Kodrat ini telah ditinggalkan dan mulai bergeser kepada bagaimana prinsip-prinsip universal hak-hak kodrati itu dipositifkan ke dalam hukum riil negara. Pada tahap ini muncul pemikiran ideologis (utilitarian) dan nonideologis objektif utopis Hans Kelsen dengan “hukum murni”nya. Arah perkembangan pemikiran itu menimbulkan tirani mayoritas di satu sisi dan penyempitan makna hukum di sisi yang lain (legisme) sehingga melahirkan kritik yang di antaranya antiutilitarian.
Pandangan Antiutilitarian yang meskipun utopis dan melanggengkan ketimpangan sosial yang ada tetapi mereka menginginkan ada satu pemerataan kebahagiaan kepada tiap-tiap individu tanpa harus melenyapkan keberadaan negara. Karena itu HAM harus seutuhnya diberi kebebasan dan kesempatan yang sama.
Berbeda antiutilitarian, Realisme hukum berpandangan perlu adanya memanifestasikan apa yang telah diperbuat oleh hukum bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Hal ini penting untuk melihat peran dan kontribusi hukum sebagai salah satu sarana perubahan sosial.
Marxian justru menghadirkan diktator proletar dalam mewujudkan HAM sosial dan ekonomi yang komunalistik. Eksploitasi sistem kapital yang merugikan kaum buruh harus dirubah dengan organisasi buruh secara massal dalam level negara sehingga dapat mengendalikan sistem kapitalis borjuis. HAM secara individual tidak dibutuhkan dalam proses itu justru sikap ateis dan totaliter harus diambil untuk mewujudkan masyarakat komunis.
Paradigma Pancasila merupakan paradigma objektif, netral, dan jalan tengah di antara pandangan yang tersebut di atas. Nilai Ketuhanan menjadi ide dasar membangun keberagamaan atas dasar toleransi dan saling menghormati. HAM universal pada tingkat konseptual diakui akan tetapi ditingkat implementasi internal berlaku partikularistik relatif.
D. Daftar Pustaka
Basah, Sjachran, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
Behn, Wolfgang, “Muhammad and The Jewes of Madina,” terjemahan dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Mensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag- Freiburg im Breisgou, 1975).
Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terjemahan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008).
Engineer, Asghar Ali, “Devolusi Negara Islam,” terjemahan dari Islamic State, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
Friedrich, Carl Joachim, “The Philosophy of Law in Historical Perspective” diterjemahkan Filsafat Hukum Perspektif Historis, ed. Nurainun Mangunsong, cet. Ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2010).
Giddens, A., The Consequences of Modernity, (Cambridge: Polity Press, 1995).
Kaelan, Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Yogyakarta, 1 Juni 2009).
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, yang terjemahannya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, cet. III, Nurainun Mangunsong (ed), (Yogyakarta: Nusa Media, 2009).
———–, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978).
Lubis, Todung Mulya, In Search of Human Rights; Legal Political dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
Maududi, Abul Ala, Islami Risayat, dinukilkan oleh Khurshid Ahmad, Islamic Publication, Lahore, 1974. Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi kedua (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
Mike Feterstone (ed.), Global Culture, Nationalism, Globalisation and Modernity, (London: Sage Publications, 1990).
Muhtaj, Majda El, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Radjawali Press, 2008).
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
Rosenau, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), Modernity and Its Future, (Cambridge: Polity Press, 1990).
Sadjali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet.ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993).
Sihombing, Frans Bona, Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Jakarta : Erlangga, 1984).
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta:UI Press, 1995).
Sumber:
Nurainun Mangungsong, 2010, Materi Kuliah Hukum dan Hak Asasi Masusia, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.